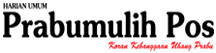Menyongsong Masa Depan: Refleksi Hari Pendidikan Nasional 2025

Dwiki Al Akhyar, S.Ud., M.Pd.--
Penulis: Dwiki Al Akhyar, S.Ud., M.Pd. (Guru Dedikatif SMK Provinsi Sumatera Selatan)
Hari Pendidikan Nasional 2025 kembali mengingatkan kita bahwa pendidikan bukan sekadar agenda tahunan, melainkan denyut nadi masa depan bangsa.
Di tengah dunia yang berubah cepat; perubahan iklim, hingga krisis sosial-ekonomi. Pendidikan Indonesia menghadapi tantangan berat. Pertanyaan mendasarnya adalah: apakah sistem pendidikan kita cukup adaptif untuk membekali generasi muda menghadapi dunia yang tak menentu ini?
Lebih dari sekadar seremoni, Hardiknas tahun ini seharusnya menjadi momentum evaluasi besar-besaran. Pendidikan kita masih berjuang dengan ketimpangan kualitas, akses, serta relevansi kurikulum terhadap kebutuhan nyata abad ke-21.
Ini bukan sekadar kritik, tetapi juga ajakan untuk melihat bahwa di tengah berbagai keterbatasan, selalu ada peluang untuk berbenah.
Oleh karena itu, opini ini mencoba membahas tiga hal pokok: tantangan pendidikan di era digital, pentingnya karakter dan kreativitas dalam kurikulum, serta peran komunitas lokal dalam memperkuat ekosistem pendidikan nasional.
Pendidikan di Era Digital: Menjawab atau Menyerah?
Teknologi digital menjanjikan revolusi besar dalam dunia pendidikan. Internet, perangkat pintar, dan platform pembelajaran daring membuka peluang baru untuk memperluas akses dan meningkatkan kualitas belajar.
Namun, realitas di lapangan jauh dari gambaran ideal. Sebagian besar sekolah di Indonesia, terutama di daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar), masih tertatih-tatih menyesuaikan diri. Akses internet belum merata, banyak guru kesulitan mengadopsi teknologi, dan infrastruktur digital kerap kali minim bahkan tidak tersedia.
Ketimpangan ini menciptakan jurang baru dalam dunia pendidikan. Siswa di kota besar yang terpapar teknologi lebih cepat berkembang, sementara siswa di daerah terpencil tertinggal jauh.
Padahal, pendidikan seharusnya menjadi alat pemersatu bangsa, bukan memperlebar kesenjangan. Jika ketimpangan digital ini terus dibiarkan, maka kita bukan hanya menghadapi masalah ketidaksetaraan, tetapi juga ancaman terhadap masa depan Indonesia sebagai bangsa yang inklusif dan berdaya saing.
Lebih dari sekadar perangkat keras dan jaringan, era pendidikan digital menuntut perubahan paradigma. Guru bukan lagi satu-satunya sumber informasi di kelas; mereka kini berperan sebagai fasilitator, mentor, dan pembimbing berpikir kritis.
Sementara itu, siswa dituntut untuk lebih aktif: mencari informasi, mengevaluasi sumber, serta mengkreasi pengetahuan baru. Sayangnya, banyak kurikulum kita masih berkutat pada metode hafalan, belum cukup membekali siswa dengan literasi digital yang kritis dan kreatif.
Menyongsong Hari Pendidikan Nasional 2025, sudah saatnya kita membangun peta jalan pendidikan digital yang lebih inklusif dan visioner. Tidak cukup hanya menyediakan tablet atau membangun laboratorium komputer.
Kita membutuhkan investasi serius dalam pengembangan kompetensi guru, penyediaan konten pembelajaran lokal yang relevan, serta dukungan kebijakan yang progresif. Tanpa strategi yang matang, upaya digitalisasi hanya akan menjadi proyek seremonial tanpa dampak jangka panjang.
Lebih jauh, kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam mendorong transformasi pendidikan digital. Pemerintah, swasta, akademisi, komunitas, hingga organisasi masyarakat sipil harus bergandengan tangan.
Pendidikan digital bukan hanya soal teknologi, tetapi tentang membangun ekosistem pembelajaran baru yang adaptif, inklusif, dan berkelanjutan. Jika kita serius, Hari Pendidikan Nasional 2025 bisa menjadi tonggak sejarah perubahan yang sesungguhnya.
Kurikulum Masa Depan: Membangun Karakter, Mengasah Kreativitas
Di tengah derasnya arus informasi dan kemajuan teknologi, karakter dan kreativitas menjadi dua kualitas utama yang membedakan individu satu dengan yang lain.
Dunia kerja masa depan tidak lagi hanya membutuhkan orang-orang yang cerdas secara akademik, melainkan mereka yang mandiri, inovatif, empatik, dan mampu bekerja sama dalam berbagai situasi.
Kompetensi teknis memang penting, tetapi kualitas kepribadian dan daya cipta akan menjadi faktor penentu kesuksesan seseorang di tengah ketidakpastian global.
Sayangnya, banyak kurikulum pendidikan kita saat ini masih berat di aspek kognitif semata. Sistem penilaian lebih banyak mengukur kemampuan menghafal ketimbang kemampuan berempati atau berpikir kreatif.
Aspek afektif dan psikomotorik—yang mencakup nilai, sikap, dan keterampilan—sering kali terpinggirkan dalam proses belajar-mengajar. Padahal, pendidikan yang berimbang antara otak, hati, dan tangan adalah pondasi untuk membangun generasi emas Indonesia.
Revitalisasi kurikulum menjadi kebutuhan mendesak. Pendidikan karakter harus dihidupkan, bukan sekadar dijadikan slogan di dinding sekolah.
Nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, rasa hormat, dan toleransi harus diintegrasikan secara nyata ke dalam seluruh aktivitas belajar, dari pelajaran akademik hingga kegiatan ekstrakurikuler.
Pendidikan karakter tidak bisa diajarkan hanya lewat ceramah; ia harus dilatih lewat pengalaman konkret dalam keseharian siswa.
Di sisi lain, kreativitas perlu diberi tempat sejajar dengan literasi dan numerasi dalam prioritas pendidikan.
Anak-anak harus diberi kesempatan untuk bertanya, bereksperimen, mengambil risiko, gagal, lalu mencoba lagi. Proses ini harus difasilitasi dengan metode pembelajaran yang inovatif, suasana kelas yang menghargai perbedaan ide, serta kultur sekolah yang mendukung keberanian berpikir di luar pakem.
Tanpa ruang untuk berkreasi, sekolah hanya akan menjadi pabrik seragam yang membunuh potensi unik setiap individu.
Karena itu, Hari Pendidikan Nasional 2025 perlu menjadi momentum refleksi sekaligus gerakan nyata untuk menata ulang prioritas pendidikan kita. Kita perlu membangun ekosistem yang tidak hanya menekankan kelulusan, tetapi juga pertumbuhan karakter dan daya cipta.
Pendidikan yang mendidik hati, mengasah pikiran, dan membebaskan imajinasi adalah kunci agar Indonesia mampu melahirkan generasi yang tidak hanya cerdas, tetapi juga beradab dan inovatif menghadapi masa depan.
Komunitas Lokal: Pilar Tersembunyi Pendidikan Nasional
Selama ini, narasi besar pendidikan nasional terlalu terpusat pada kebijakan yang lahir dari pemerintah pusat. Semua seolah berjalan satu arah: dari atas ke bawah.
Padahal, kekuatan pendidikan sejati sering kali justru tumbuh dari bawah, dari gerakan akar rumput: komunitas lokal, keluarga, dan lingkungan sekitar. Desa-desa, kampung kota, hingga komunitas adat sebenarnya menyimpan kearifan lokal yang bisa memperkaya dan memperdalam makna pendidikan.
Dalam komunitas lokal, pendidikan sering hadir dalam bentuk yang lebih membumi dan kontekstual. Program literasi berbasis desa, kelas keterampilan yang digagas oleh kelompok warga, atau budaya gotong royong dalam membantu siswa yang hampir putus sekolah—semuanya adalah bentuk pendidikan yang hidup dan relevan.
Sayangnya, inisiatif-inisiatif semacam ini kerap luput dari perhatian negara dan tidak mendapat dukungan yang memadai.
Memberdayakan komunitas lokal berarti mempercayai bahwa pendidikan bukan monopoli sekolah formal. Pendidikan adalah proses sosial yang melibatkan semua elemen masyarakat, bukan hanya tugas guru di ruang kelas.
Ketika komunitas diberi ruang untuk berkreasi dan berinovasi dalam pendidikan, sistem pendidikan nasional menjadi lebih berwarna, berakar kuat, dan berkelanjutan. Ini juga membuat pendidikan lebih mampu menjawab kebutuhan nyata yang dihadapi anak-anak di setiap daerah.
Hari Pendidikan Nasional 2025 seharusnya menjadi momentum untuk memperluas kanal kolaborasi antara pemerintah dan komunitas lokal.
Pemerintah perlu membuka ruang dialog yang setara, mendengarkan aspirasi masyarakat, dan mendukung inisiatif pendidikan dari bawah. Melibatkan tokoh masyarakat, orang tua, alumni, bahkan pengusaha lokal, bisa menghidupkan kembali semangat belajar kolektif yang lebih kuat dan organik.
Dengan memperkuat peran komunitas, pendidikan Indonesia bisa menjadi lebih adaptif terhadap perubahan zaman tanpa kehilangan akar budayanya.
Pendidikan tidak lagi sekadar transfer pengetahuan dari guru ke murid, tetapi menjadi gerakan sosial yang melibatkan semua pihak. Inilah jalan untuk membangun ekosistem pendidikan yang tidak hanya pintar secara akademik, tetapi juga berdaya, berbudaya, dan berakar kuat di tanahnya sendiri. (*)